 |
| DokFoto: HydraZone |
Pada masyarakat dan kebudayaan manapun pasti dikenal apa yang disebut sebagai harga diri, baik dalam konsep individual maupun kelompok, tidak terkecuali dalam masyarakat dan kebudayaan Madura. Tulisan ini mencoba memahami dan membahas konsep harga diri dalam masyarakat dan kebudayaan Madura dengan cara antara lain melihat hubungan relasionalnya dengan beberapa peristiwa sosial budaya yang secara empirik terjadi dalam kehidupan sehari-hari orang Madura.
Orang Madura akan merasa malo atau terhina jika harga dirinya dilecehkan oleh (atau sebagai akibat dari) perbuatan orang lain. Pelecehan harga diri ini sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri mereka. Padahal kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan statusnya (social role and status) dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku. Peran dan status sosial ini dalam prakteknya tidak cukup hanya disadari oleh individu yang bersangkutan melainkan harus mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya. Bahkan pada setiap bentuk relasi sosial antara orang yang satu dengan yang lainnya harus saling menghargai peran dan status sosial masing-masing. Tapi ada kalanya hal ini tidak dipatuhi. Bagi orang Madura tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang tada’ ajhina (tidak bermakna secara sosial dan budaya) yang pada gilirannya menimbulkan perasaan malo.
Dalam bahasa Madura selain kata malo juga terdapat kata todus. Dalam bahasa Indonesia kedua kata ini selalu diterjemahkan sebagai malu. Tapi, dalam konteks kehidupan sosial budaya Madura, antara malo dan todus mempunyai pengertian yang sangat berbeda. Malo bukanlah suatu bentuk lain dari ungkapan perasaan todus. Pada dasarnya todus lebih merupakan suatu ungkapan keengganan (tidak ada kemauan) melakukan sesuatu karena adanya berbagai kendala yang bersifat sosial-budaya. Misalnya, menurut adat kebiasaan yang berlaku di Madura seorang menantu ketika sedang berbicara dengan mertuanya tidak boleh menatap wajahnya secara langsung. Semua menantu akan merasa todus jika berbicara kepada mertuanya dengan cara seperti itu. Jika hal itu dilakukan maka secara sosial menantu tersebut kemudian akan disebut sebagai orang ta’ tao atoran atau janggal (tidak mengerti etika kesopanan) sehingga menimbulkan perasaan todus (tidak tahu malu).
Dengan demikian, biasanya todus muncul dari dalam diri seseorang sebagai akibat dari tindakan dirinya sendiri yang menyimpang dari aturan-aturan normatif. Sebaliknya, malo muncul lebih sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya sehingga yang bersangkutan merasa menjadi tada’ ajhina. Orang Madura yang diperlakukan seperti itu sama artinya dengan dilecehkan harga dirinya kemudian mereka akan selalu melakukan tindakan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan itu. Kadangkala tindakan perlawanan atau resistensi tersebut cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrimnya adalah pembunuhan) tergantung pada berat ringannya pelecehan harga diri yang dialami. Suatu ungkapan yang berbunyi ango’an poteya tolang etembhang poteya mata (lebih baik mati daripada harus menanggung perasaan malo) menunjukkan indikasi tentang hal itu.
Tindakan resistensi yang sangat keras biasanya tidak akan terjadi pada orang Madura yang berada dalam situasi atau merasa todus karena yang bersangkutan tidak merasa dilecehkan harga dirinya. Dengan demikian ada tidaknya tindakan pelecehan harga diri merupakan indikator penting untuk membedakan antara todus dan malo. Dalam realitas sosial budaya, pada umumnya todus cenderung hanya mencakup lingkup individual, sebaliknya malo dapat tereskalasi ke lingkup yang lebih luas (keluarga dan masyarakat). Hal ini biasanya terjadi apabila menyangkut gangguan terhadap isteri.
Bagi orang Madura, tindakan mengganggu kehormatan isteri selalu dimaknai sebagai tindakan arosak atoran (merusak tatanan sosial). Itu sebabnya, gangguan terhadap isteri akan dimaknai pula sebagai pelecehan terhadap harga diri secara kolektif. Perasaan malo akibat terjadinya gangguan terhadap isteri yang akhirnya bersifat kolektif tersebut selain memiliki relasi sangat signifikan dengan sistem perkawinan matrilokal dan uxorilokal atau kombinasi antara keduanya yang masih berlaku dalam masyarakat Madura juga tercermin dalam pola pemukiman taneyan lanjhang, formasi struktur rumah tradisional, serta tradisi kin group endogamy. Makna substantif dari semuanya ini, perempuan Madura selalu mendapat perhatian serta proteksi kultural secara khusus mulai dari lingkup keluarga sampai ke lingkup sosial. Ini semua pada akhirnya menjadi faktor penguat terjadinya resistensi yang sangat keras berupa pembunuhan terhadap orang yang melakukan gangguan pada isteri.
Memahami konflik yang berpangkal pada pelecehan harga diri orang Madura akan semakin proporsional dan kontekstual bila dipahami pula dua konsep penting yang berkaitan dengan relasi sosial yang dibangun orang Madura yaitu teman (bhala, kanca) dan musuh (moso). Konsep teman merujuk pada relasi sosial dengan derajat keakraban pada taraf tertentu hingga ke derajat paling tinggi; sebaliknya, konsep musuh merupakan perwujudan relasi sosial tanpa keakraban sama sekali atau paling tidak pada taraf paling rendah. Dengan kata lain, kehidupan harmonis muncul karena dominannya semangat pertemanan (friendship); sebaliknya, kondisi kehidupan yang bernuansa konflik ditandai oleh dominasi perasaan permusuhan (enmity).
Menurut pengertian orang Madura, bhala selain menunjuk pada pengertian teman juga menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sehingga bhala sering kali diartikan identik atau sama dengan taretan.
Dengan demikian, taretan dalem (kerabat inti atau core kin) sering kali disebut juga sebagai bhala dalem; sedangkan taretan semma’ (kerabat dekat atau close kin) sebagai bhala semma’ dan taretan jhau (kerabat jauh atau peripheral kin) sebagai bhala jhau. Dalam konteks ini ada bhala dalam arti taretan atau diistilahkan dengan “bhala taretan” dan ada pula bhala dalam arti bukan termasuk taretan atau dalam terminologi lain biasa disebut kanca (teman). Kanca bisa berasal dari berbagai macam lingkungan sosial, di antaranya teman dari lingkungan ketetanggaan (kanca tatanggha), teman dari lingkungan kerja (kanca lako), teman dari lingkungan remo (kanca remo), dan dari lingkungan sosial lainnya.
Mereka yang dikategorikan sebagai kanca adalah orang-orang yang saling terikat oleh hubungan sosial dan emosional. Jika kualitas hubungan yang terjalin sebatas hubungan pertemanan biasa orang Madura menyebutnya kanca biyasa, tapi jika kualitas hubungan menjadi akrab disebut kanca rapet. Bahkan jika kualitas hubungan sampai mencapai tingkatan yang sangat akrab sehingga hampir tidak berbeda dengan hubungan persaudaraan maka kanca atau kanca rapet dapat dianggap dan diperlakukan juga sebagai anggota keluarga atau taretan.
Sebaliknya, adakalanya anggota keluarga (taretan termasuk taretan ereng, persaudaraan karena adanya ikatan perkawinan) dapat dianggap dan diperlakukan sebagai oreng (bukan keluarga) jika kualitas hubungan kekerabatannya sangat rendah misalnya karena adanya perselisihan dengan anggota keluarga yang lain. Hal yang demikian dalam ungkapan bahasa Madura disebut oreng dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng (artinya: orang lain yang bukan keluarga dapat dianggap sebagai saudara, sebaliknya saudara sendiri dapat dianggap sebagai bukan keluarga). Bahkan jika perselisihan tersebut menyebabkan hilangnya hubungan kekerabatan maka tidak mustahil anggota keluarga tersebut dianggap sebagai moso (musuh). Dalam situasi semacam ini, tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik kekerasan intra-keluarga. Dengan demikian, kualitas hubungan yang terjalin sangat ditentukan oleh kualitas pengakuan sekaligus penghargaan terhadap kapasitas diri masing-masing individu.
Kebalikan daripada teman (bhala) adalah musuh (moso). Moso dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu moso dalem dan moso lowar. Moso dalem adalah musuh dari lingkungan keluarga sendiri, sedangkan moso lowar adalah musuh yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan atau bukan dari lingkungan keluarga sendiri. Baik moso lowar maupun moso dalem masih dibedakan lagi antara moso mata dan moso ate.
Moso mata adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara terang-terangan diperlakukan sebagai musuh sehingga konflik dapat meledak dimana saja dan kapan saja. Itu sebabnya, masing-masing pihak harus selalu dalam keadaan waspada dan siap siaga mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan terburuk (konflik kekerasan). Moso ate adalah seseorang atau sekelompok orang yang dalam pergaulan sehari-hari tidak secara terang-terangan diperlakukan sebagai musuh tapi diperlakukan seolah-olah sebagai teman. Bahkan adakalanya hubungan pertemanan terkesan sangat erat bagaikan sahabat karib (kanca rapet). Tanda-tanda atau isyarat-isyarat permusuhan sama sekali tidak diperlihatkan. Akibatnya, biasanya orang yang sebenarnya adalah musuh ini menjadi lengah terhadap ancaman tindakan kekerasan yang akan menimpanya.
Konsep bhala dan moso dalam makna yang hampir sama dikenal juga oleh masyarakat Sulu – khususnya suku Tausug di Filipina Selatan dari suatu hasil penelitian antropologis tentang kekerasan (violence) yang pernah dilakukan oleh Thomas M. Kiefer (1972). Pertemanan (friendship, bagay) dan permusuhan (enmity, bantah) merupakan dua konsep yang selalu muncul dalam organisasi sosial masyarakat ini. Kiefer merinci macam-macam pertemanan dan permusuhan tersebut menjadi sembilan kategori, yaitu: bagay (close friend); bagay magtaymanghud (ritual friend or “friend like brother”); bagay-bagay (casual friend); gapi (ally); bantah (enemy); tau hansipak (opponent); tindug (retainer or follower); bata’an (bodyguard); dan tau ha ut (neutral).
Pada masyarakat suku Tausug selain terlihat secara jelas perbedaan antara kekerabatan (kinship) dan pertemanan (friendship) namun ada kalanya kedua konsep tersebut dimaknai sama sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat Madura. Dalam masyarakat suku Tausug hal itu disebut bagay magtay manghud (teman bagaikan saudara) sedangkan dalam masyarakat Madura, sebagaimana telah disinggung di bagian lain di muka, tercermin dalam suatu ungkapan: oreng dhaddhi taretan.
Dalam konteks itu, satu hal sangat penting yang perlu disadari dan dipahami adalah makna hubungan pertemanan dalam masyarakat Madura – demikian pula dalam masyarakat suku Tausug – senantiasa dilandasi oleh semangat resiprokal. Dengan demikian, apabila hubungan pertemanan semacam itu dikelola dengan baik dan senantisa dijadikan semangat, referensi dan landasan dalam kehidupan sosial oleh orang Madura, maka konflik (kekerasan) sudah pasti dapat diantisipasi dan sekaligus dicegah sedini mungkin. Pada gilirannya, kehidupan sosial orang Madura niscaya akan selalu dalam suasana yang nyaman, sejuk, dan teduh penuh kedamaian sebagaimana makna ungkapan rampa’ naong, baringen korong. Ungkapan ini semakin jelas relevansi dan urgensinya dalam situasi sosial politik Madura menjelang pelaksanaan Pemilu 2004.
Orang Madura akan merasa malo atau terhina jika harga dirinya dilecehkan oleh (atau sebagai akibat dari) perbuatan orang lain. Pelecehan harga diri ini sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri mereka. Padahal kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan statusnya (social role and status) dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku. Peran dan status sosial ini dalam prakteknya tidak cukup hanya disadari oleh individu yang bersangkutan melainkan harus mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya. Bahkan pada setiap bentuk relasi sosial antara orang yang satu dengan yang lainnya harus saling menghargai peran dan status sosial masing-masing. Tapi ada kalanya hal ini tidak dipatuhi. Bagi orang Madura tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang tada’ ajhina (tidak bermakna secara sosial dan budaya) yang pada gilirannya menimbulkan perasaan malo.
Dalam bahasa Madura selain kata malo juga terdapat kata todus. Dalam bahasa Indonesia kedua kata ini selalu diterjemahkan sebagai malu. Tapi, dalam konteks kehidupan sosial budaya Madura, antara malo dan todus mempunyai pengertian yang sangat berbeda. Malo bukanlah suatu bentuk lain dari ungkapan perasaan todus. Pada dasarnya todus lebih merupakan suatu ungkapan keengganan (tidak ada kemauan) melakukan sesuatu karena adanya berbagai kendala yang bersifat sosial-budaya. Misalnya, menurut adat kebiasaan yang berlaku di Madura seorang menantu ketika sedang berbicara dengan mertuanya tidak boleh menatap wajahnya secara langsung. Semua menantu akan merasa todus jika berbicara kepada mertuanya dengan cara seperti itu. Jika hal itu dilakukan maka secara sosial menantu tersebut kemudian akan disebut sebagai orang ta’ tao atoran atau janggal (tidak mengerti etika kesopanan) sehingga menimbulkan perasaan todus (tidak tahu malu).
Dengan demikian, biasanya todus muncul dari dalam diri seseorang sebagai akibat dari tindakan dirinya sendiri yang menyimpang dari aturan-aturan normatif. Sebaliknya, malo muncul lebih sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya sehingga yang bersangkutan merasa menjadi tada’ ajhina. Orang Madura yang diperlakukan seperti itu sama artinya dengan dilecehkan harga dirinya kemudian mereka akan selalu melakukan tindakan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan itu. Kadangkala tindakan perlawanan atau resistensi tersebut cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrimnya adalah pembunuhan) tergantung pada berat ringannya pelecehan harga diri yang dialami. Suatu ungkapan yang berbunyi ango’an poteya tolang etembhang poteya mata (lebih baik mati daripada harus menanggung perasaan malo) menunjukkan indikasi tentang hal itu.
Tindakan resistensi yang sangat keras biasanya tidak akan terjadi pada orang Madura yang berada dalam situasi atau merasa todus karena yang bersangkutan tidak merasa dilecehkan harga dirinya. Dengan demikian ada tidaknya tindakan pelecehan harga diri merupakan indikator penting untuk membedakan antara todus dan malo. Dalam realitas sosial budaya, pada umumnya todus cenderung hanya mencakup lingkup individual, sebaliknya malo dapat tereskalasi ke lingkup yang lebih luas (keluarga dan masyarakat). Hal ini biasanya terjadi apabila menyangkut gangguan terhadap isteri.
Bagi orang Madura, tindakan mengganggu kehormatan isteri selalu dimaknai sebagai tindakan arosak atoran (merusak tatanan sosial). Itu sebabnya, gangguan terhadap isteri akan dimaknai pula sebagai pelecehan terhadap harga diri secara kolektif. Perasaan malo akibat terjadinya gangguan terhadap isteri yang akhirnya bersifat kolektif tersebut selain memiliki relasi sangat signifikan dengan sistem perkawinan matrilokal dan uxorilokal atau kombinasi antara keduanya yang masih berlaku dalam masyarakat Madura juga tercermin dalam pola pemukiman taneyan lanjhang, formasi struktur rumah tradisional, serta tradisi kin group endogamy. Makna substantif dari semuanya ini, perempuan Madura selalu mendapat perhatian serta proteksi kultural secara khusus mulai dari lingkup keluarga sampai ke lingkup sosial. Ini semua pada akhirnya menjadi faktor penguat terjadinya resistensi yang sangat keras berupa pembunuhan terhadap orang yang melakukan gangguan pada isteri.
Memahami konflik yang berpangkal pada pelecehan harga diri orang Madura akan semakin proporsional dan kontekstual bila dipahami pula dua konsep penting yang berkaitan dengan relasi sosial yang dibangun orang Madura yaitu teman (bhala, kanca) dan musuh (moso). Konsep teman merujuk pada relasi sosial dengan derajat keakraban pada taraf tertentu hingga ke derajat paling tinggi; sebaliknya, konsep musuh merupakan perwujudan relasi sosial tanpa keakraban sama sekali atau paling tidak pada taraf paling rendah. Dengan kata lain, kehidupan harmonis muncul karena dominannya semangat pertemanan (friendship); sebaliknya, kondisi kehidupan yang bernuansa konflik ditandai oleh dominasi perasaan permusuhan (enmity).
Menurut pengertian orang Madura, bhala selain menunjuk pada pengertian teman juga menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sehingga bhala sering kali diartikan identik atau sama dengan taretan.
Dengan demikian, taretan dalem (kerabat inti atau core kin) sering kali disebut juga sebagai bhala dalem; sedangkan taretan semma’ (kerabat dekat atau close kin) sebagai bhala semma’ dan taretan jhau (kerabat jauh atau peripheral kin) sebagai bhala jhau. Dalam konteks ini ada bhala dalam arti taretan atau diistilahkan dengan “bhala taretan” dan ada pula bhala dalam arti bukan termasuk taretan atau dalam terminologi lain biasa disebut kanca (teman). Kanca bisa berasal dari berbagai macam lingkungan sosial, di antaranya teman dari lingkungan ketetanggaan (kanca tatanggha), teman dari lingkungan kerja (kanca lako), teman dari lingkungan remo (kanca remo), dan dari lingkungan sosial lainnya.
Mereka yang dikategorikan sebagai kanca adalah orang-orang yang saling terikat oleh hubungan sosial dan emosional. Jika kualitas hubungan yang terjalin sebatas hubungan pertemanan biasa orang Madura menyebutnya kanca biyasa, tapi jika kualitas hubungan menjadi akrab disebut kanca rapet. Bahkan jika kualitas hubungan sampai mencapai tingkatan yang sangat akrab sehingga hampir tidak berbeda dengan hubungan persaudaraan maka kanca atau kanca rapet dapat dianggap dan diperlakukan juga sebagai anggota keluarga atau taretan.
Sebaliknya, adakalanya anggota keluarga (taretan termasuk taretan ereng, persaudaraan karena adanya ikatan perkawinan) dapat dianggap dan diperlakukan sebagai oreng (bukan keluarga) jika kualitas hubungan kekerabatannya sangat rendah misalnya karena adanya perselisihan dengan anggota keluarga yang lain. Hal yang demikian dalam ungkapan bahasa Madura disebut oreng dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng (artinya: orang lain yang bukan keluarga dapat dianggap sebagai saudara, sebaliknya saudara sendiri dapat dianggap sebagai bukan keluarga). Bahkan jika perselisihan tersebut menyebabkan hilangnya hubungan kekerabatan maka tidak mustahil anggota keluarga tersebut dianggap sebagai moso (musuh). Dalam situasi semacam ini, tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik kekerasan intra-keluarga. Dengan demikian, kualitas hubungan yang terjalin sangat ditentukan oleh kualitas pengakuan sekaligus penghargaan terhadap kapasitas diri masing-masing individu.
Kebalikan daripada teman (bhala) adalah musuh (moso). Moso dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu moso dalem dan moso lowar. Moso dalem adalah musuh dari lingkungan keluarga sendiri, sedangkan moso lowar adalah musuh yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan atau bukan dari lingkungan keluarga sendiri. Baik moso lowar maupun moso dalem masih dibedakan lagi antara moso mata dan moso ate.
Moso mata adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara terang-terangan diperlakukan sebagai musuh sehingga konflik dapat meledak dimana saja dan kapan saja. Itu sebabnya, masing-masing pihak harus selalu dalam keadaan waspada dan siap siaga mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan terburuk (konflik kekerasan). Moso ate adalah seseorang atau sekelompok orang yang dalam pergaulan sehari-hari tidak secara terang-terangan diperlakukan sebagai musuh tapi diperlakukan seolah-olah sebagai teman. Bahkan adakalanya hubungan pertemanan terkesan sangat erat bagaikan sahabat karib (kanca rapet). Tanda-tanda atau isyarat-isyarat permusuhan sama sekali tidak diperlihatkan. Akibatnya, biasanya orang yang sebenarnya adalah musuh ini menjadi lengah terhadap ancaman tindakan kekerasan yang akan menimpanya.
Konsep bhala dan moso dalam makna yang hampir sama dikenal juga oleh masyarakat Sulu – khususnya suku Tausug di Filipina Selatan dari suatu hasil penelitian antropologis tentang kekerasan (violence) yang pernah dilakukan oleh Thomas M. Kiefer (1972). Pertemanan (friendship, bagay) dan permusuhan (enmity, bantah) merupakan dua konsep yang selalu muncul dalam organisasi sosial masyarakat ini. Kiefer merinci macam-macam pertemanan dan permusuhan tersebut menjadi sembilan kategori, yaitu: bagay (close friend); bagay magtaymanghud (ritual friend or “friend like brother”); bagay-bagay (casual friend); gapi (ally); bantah (enemy); tau hansipak (opponent); tindug (retainer or follower); bata’an (bodyguard); dan tau ha ut (neutral).
Pada masyarakat suku Tausug selain terlihat secara jelas perbedaan antara kekerabatan (kinship) dan pertemanan (friendship) namun ada kalanya kedua konsep tersebut dimaknai sama sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat Madura. Dalam masyarakat suku Tausug hal itu disebut bagay magtay manghud (teman bagaikan saudara) sedangkan dalam masyarakat Madura, sebagaimana telah disinggung di bagian lain di muka, tercermin dalam suatu ungkapan: oreng dhaddhi taretan.
Dalam konteks itu, satu hal sangat penting yang perlu disadari dan dipahami adalah makna hubungan pertemanan dalam masyarakat Madura – demikian pula dalam masyarakat suku Tausug – senantiasa dilandasi oleh semangat resiprokal. Dengan demikian, apabila hubungan pertemanan semacam itu dikelola dengan baik dan senantisa dijadikan semangat, referensi dan landasan dalam kehidupan sosial oleh orang Madura, maka konflik (kekerasan) sudah pasti dapat diantisipasi dan sekaligus dicegah sedini mungkin. Pada gilirannya, kehidupan sosial orang Madura niscaya akan selalu dalam suasana yang nyaman, sejuk, dan teduh penuh kedamaian sebagaimana makna ungkapan rampa’ naong, baringen korong. Ungkapan ini semakin jelas relevansi dan urgensinya dalam situasi sosial politik Madura menjelang pelaksanaan Pemilu 2004.
Di Tulis Oleh : Dr. A. Latief Wiyata
Sumber : Lontarmadura.com

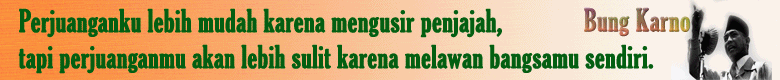




Post a Comment